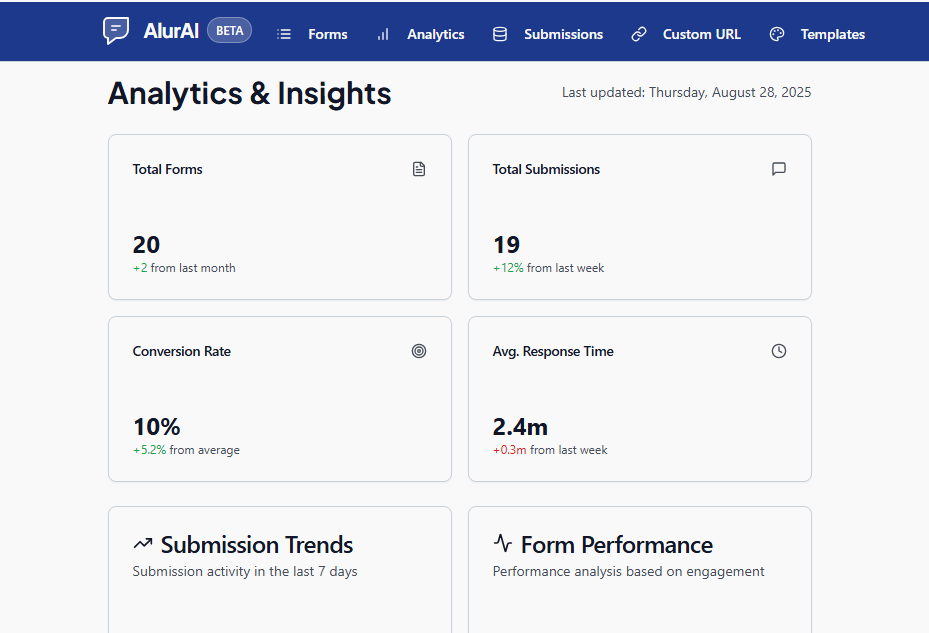Oleh : Mifathol Anwar*
machan – Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena di mana banyak pelaku usaha mulai menggantikan layanan pelanggan konvensional dengan chatbot, sebagai bentuk interaksi awal antara konsumen dan brand. Tren ini tidak hanya terjadi di sektor e-commerce, tetapi juga merambah ke bidang kesehatan, pendidikan, hingga layanan pemerintahan. Menurut Forbes, sekitar 80% bisnis di seluruh dunia berencana mengandalkan chatbot untuk meningkatkan pengalaman pelanggan mereka (Ningtyas, 2020). Teknologi ini dianggap lebih efektif dan efisien karena mampu memberikan layanan tanpa batas waktu, selama 24 jam.
Terlebih lagi, dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI), chatbot kini bisa merespons pelanggan dengan lebih cepat, cerdas, bahkan terkesan personal. Namun, sebagai mahasiswa doktoral di bidang ilmu komunikasi, saya mempertanyakan: apakah komunikasi tanpa emosi melalui chatbot benar-benar mampu menggantikan kualitas layanan yang diberikan oleh manusia?
Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori komunikasi interpersonal. Menurut Arvind Kumar (dalam Warta Ilmiah Populer Komunikasi dalam Pembangunan, Vol. 9, No. 1, 2006), terdapat lima ciri komunikasi interpersonal yang efektif: keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Kelima elemen ini menjadi dasar dalam membangun relasi yang hangat dan bermakna antara dua pihak.
Dalam konteks layanan pelanggan, komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga membangun kedekatan emosional dan kepercayaan, yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sebaliknya, komunikasi melalui chatbot bersifat linier, impersonal, dan minim nuansa emosi. Bahkan, dalam banyak kasus, chatbot gagal memberikan solusi yang relevan atau adaptif. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa layanan teknologi, sejauh ini, belum mampu menggantikan dimensi emosional yang hanya bisa dihadirkan melalui interaksi manusia.
Saya sendiri pernah mengalami frustrasi saat berhadapan dengan layanan chatbot dari salah satu bank nasional. Ketika saya menyampaikan keluhan, jawaban yang diberikan tidak sesuai harapan dan gagal memberikan solusi yang memadai. Lebih dari itu, akses menuju layanan pelanggan manusia pun sangat terbatas, sehingga memperburuk pengalaman komunikasi saya sebagai konsumen.
Beberapa brand e-commerce besar seperti Shopee dan TikTokShop by Tokopedia tampaknya mulai menyadari keterbatasan ini. Mereka kini mengintegrasikan pendekatan hybrid, menggunakan chatbot untuk menangani pertanyaan dasar, dan memberikan opsi “Chat dengan Agen” ketika permasalahan lebih kompleks muncul.
Hal ini membuktikan bahwa meskipun teknologi dapat membantu efisiensi layanan, sentuhan emosional dan empatik dari manusia tetap dibutuhkan dalam konteks komunikasi bisnis yang melibatkan interaksi interpersonal secara lebih dalam.
Dengan hadirnya teknologi AI yang semakin berkembang, para pengembang juga dituntut untuk merancang chatbot yang lebih personal, adaptif, dan mampu menampilkan respons yang simpatik dan empatik. Harapannya, chatbot bukan hanya sekadar alat bantu teknis, tetapi juga bisa menjadi jembatan komunikasi yang lebih manusiawi.
Bagi dunia komunikasi bisnis, ini menjadi catatan penting: kecepatan dan efisiensi bukanlah segalanya. Di tengah era digital yang serba otomatis, nilai-nilai emosional dan sentuhan kemanusiaan tetap tak tergantikan.
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta, sekaligus Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Annuqayah Sumenep